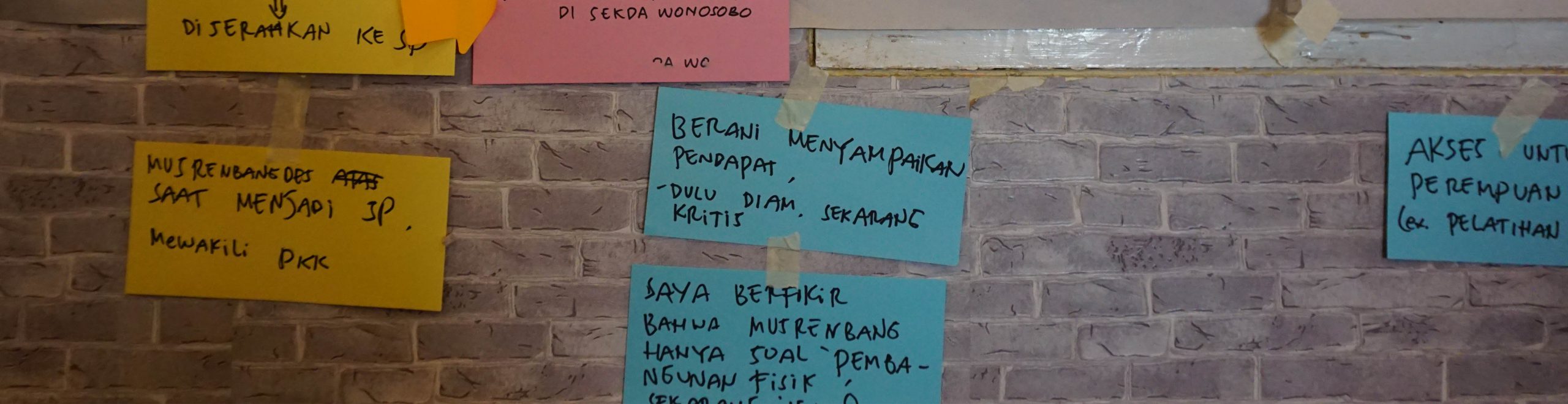
Daftar Isi
Terimakasih kepada seluruh peserta review digital RAN P3AKS yang sudah mendedikasikan waktu untuk memberi masukan penting. Berikut draft hasil kesimpulan dan rekomendasi yang kami olah dari masukan kawan-kawan di 4 ruang diskusi yaitu pilar pencegahan, penanganan, pemberdayaan dan partisipasi, dan satu ruang tentang extremisme. Kami berharap kawan-kawan dapat mencermati berdasarkan masukan yang pernah dimunculkan dalam review digital, untuk memastikan tidak ada poin penting yang terlewat, dan juga mengkoreksi kalau ada formulasi yang kurang tepat.
Masukan akan berlangsung dari Minggu 06 September 2020 dan akan ditutup pada Sabtu 12 September 2020 Pukul 24.00 Wib. Setelah itu akan kami sempurnakan untuk menjadi masukan pada arah kebijakan perdamaian dan keamanan di Indonesia, khususnya penyusunan RAN P3AKS tahab 2.
Terimakasih dan hormat kami
Yuniyanti Chuzaifah dan Fitriani
1. Capaian dan Arti Strategis RAN P3AKS: Catatan Pengantar
Indonesia telah mengadopsi agenda Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (Women, Peace and Security) melalui Peraturan Presiden No. 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di bawah payung hukum Undang-Undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Untuk melaksanakan Perpres No. 18 tahun 2014 tersebut, pemerintah mengeluarkan “Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) 2014-2019”. Pencapaian ini menambah instrumen regulasi dalam institusionalisasi hak-hak perempuan di Indonesia sejak reformasi 1998 yang mengacu pada CEDAW dan mendapat apresiasi dari banyak pihak di dalam dan luar negeri. RAN menjadi instrumen yang menguatkan kerja berbagai lembaga negara maupun non negara, dalam mendorong upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam penanganan konflik sosial. Untuk menyebut sebagai contoh, adalah penggunaan instrumen RAN oleh Komnas Perempuan, dalam mendorong penyelesaian berbagai kasus konflik untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan (seperti dalam kasus Kendeng, Seko dan konflik sosial lainnya). Begitu juga bagi banyak organisasi masyarakat sipil, RAN telah menjadi instrumen yang menguatkan upaya advokasi yang dilakukan.
Sejak diluncurkannya tahun 2014, Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional yang didukung oleh organisasi-organisasi sipil telah melakukan uji coba Rencana Aksi Daerah (RAD) di beberapa provinsi. Perjalanan mendorong RAN dan RAD ini juga menunjukkan upaya menerjemahkan instrumen global dengan kondisi dan kebutuhan nasional dan daerah. Kontekstualisasi instrumen global bisa ditunjukkan dengan menemukan pengalaman-pengalaman di tingkat komunitas dan lokal, terutama terkait dengan pengalaman perempuan dalam menghadapi konflik: dampak konflik berbasis gender yang membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan, serta pentingnya memastikan keterlibatan perempuan sebagai agensi dalam mendorong perdamaian dan penanganan konflik. Pada sisi yang lain, inisiatif lokal juga menjadi sumber dan referensi penting dalam perjalanan dan perkembangan instrumen global Resolusi 1325. Melalui ini, kita melihat pertautan yang bersifat timbal balik antara instrumen dan praktek global dan lokal.Terwujudnya RAN P3AKS dan RAD menggambarkan bahwa demokrasi telah memfasilitasi relasi pemerintah dan masyarakat sipil dengan baik sehingga membuka ruang komunikasi yang lebih setara. Hal ini juga menunjukkan, terbangunnya kepemilikan bersama baik oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil terhadap RAN / RAD ini. Dalam inisiatif mendorong perubahan, kepemilikan bersama adalah modalitas penting untuk mendorong keberlanjutan upaya mendorong perubahan dalam jangka panjang.
Periode RAN P3AKS 2014-2019 telah selesai. Terinspirasi oleh studi global 15 tahun pelaksanaan Resolusi 1325 yang dilakukan pada tahun 2015, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang selama ini telah bekerja mempromosikan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender melaksanakan “Konsultasi Digital Nasional untuk Mengkaji Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019”. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RAN P3AKS periode berikutnya.
2. Metodologi Review Digital
Konsultasi digital dalam rangka mengevaluasi RAN P3AKS 2014-2019 dilakukan dengan tujuan untuk:
- Melihat pelaksanaan Perpres No. 18 tahun 2014 di 15 provinsi yang merupakan lokasi uji coba Rencana Aksi Daerah;
- Mengkaji hal-hal lain seputar agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan yang belum dibahas dalam RAN, tetapi dalam lima tahun terakhir kuat muncul di daerah; dan
- Mengevaluasi adanya perubahan sifat dasar konflik (nature of conflict), akar masalah dan aktor-aktor baru yang terlibat dalam konflik
- Mencari rekomendasi untuk mendorong efektivitas, relevansi, efisiensi dan keberlangsungan jangka panjang agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di Indonesia
Sejumlah tahapan untuk menjalankan review pelaksanaan RAN P3AKS 2014-2019 telah dilangsungkan pada bulan Maret 2020 dengan melibatkan sejumlah organisasi, think tank dan juga para ahli yang terlibat sejak awal dalam perumusan RAN. Namun terkendala untuk menjangkau 34 provinsi di seluruh Indonesia dan pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas, hadir inovasi untuk membawa konsultasi ke ranah digital yang diharapkan mampu menjangkau partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat sipil yang lebih luas bila dibandingkan dengan melakukan pertemuan diskusi tatap muka fisik.
Konsultasi digital dilangsungkan secara daring melalui laman situs https://wps-indonesia.com/ mulai dari 26 Juli hingga 31 Agustus 2020. Terdapat lima ruang diskusi di mana peserta bisa ikut memberi masukan, yakni
- Pencegahan Konflik dan Keterlibatan Perempuan;
- Penanganan Konflik dan Pemulihan Korban Perempuan dan Anak;
- Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dan Anak;
- Perempuan dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan; serta
- Rekomendasi Publik.
Diskusi dilakukan secara tertulis di laman situs, selain itu peserta diskusi juga dapat mengirimkan dokumen, pesan gambar, serta data yang bisa dibagikan melalui lampiran. Metode pengumpulan informasi juga dilakukan dengan melakukan diskusi terbatas kelompok (focus group discussion) secara online melalui ruang meeting online Zoom baik berdasarkan tema, antara lain konflik sumber daya alam dan isu kontra terorisme, maupun melibatkan kelompok yang dikhawatirkan terkendala mengakses review digital ini, khususnya komunitas korban.
Meski konsultasi dilakukan secara digital, namun diskusi baik tertulis maupun secara langsung tatap muka online berjalan secara efektif disebabkan karena pandemi Covid-19 telah membiasakan diskusi melalui jalur elektronik. Atas kondisi ini, pembahasan konsultasi digital kemudian mengikutsertakan aspek-aspek baru dari dinamika sosial yang berkembang untuk bisa diintegrasikan dalam implementasi RAN P3AKS. Sebagai contoh adalah ekstremisme kekerasan yang berdampak pada agensi perempuan yaitu mencerminkan pergeseran norma gender dalam terorisme dan kontra-terorisme. Berikut ini adalah kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan.
3 Kesimpulan
3.1. Poin-poin kesimpulan umum
Kompleksitas dan pola baru konflik :
Beberapa akar konflik yang dibahas dalam diskusi adalah konflik jangka panjang dan massif seperti konflik sumber daya alam yang minim dibahas dalam RAN P3AKS. Konflik lain yang tak kunjung usai adalah ketegangan antar umat beragama (seperti kasus GKI Yasmin, Syiah, Gafatar, penghayat) dan persekusi terhadap kelompok minoritas masyarakat (antara lain terhadap etnis minoritas, masyarakat adat, juga kelompok rentan diskriminasi lain). Review ini juga mengidentifikasi potensi konflik periodik yang ditimbulkan dari persaingan kepentingan politik dalam pemilihan umum, baik nasional maupun daerah. Konflik sudah turun ke desa, menghadap-hadapkan antar masyarakat, namun tidak diimbangi dengan kemampuan mendamaikan di tingkat komunitas. Isu krusial lain adalah soal radikalisme dan ekstrimisme kekerasan yang dirasakan belum punya formula penyelesaian yang strategis.
Makna aman dan peran keamanan :
Review ini menyoal peran militer dan polisi yang harus memiliki kacamata baru dalam memaknai rasa aman dan tidak mengedepankan tindakan represif yang berpotensi menyisakan konflik jangka panjang. Mengutamakan keamanan manusia bersanding dengan keamanan negara menjadi kunci. Membangun rasa aman juga dapat dengan upaya dialog damai dan langkah untuk penyelesaian konflik yang tidak meningkatkan durasi konflik, (seperti dalam konflik di Papua atau konflik sumber daya alam yang menonjol terkait dengan komoditas tambang dan sawit). Lebih jauh lagi pemahaman sensitif gender di kalangan aparat keamanan menjadi kunci dalam penanganan konflik , secara khusus harus mempunyai pengetahuan atas UU P3AKS dan RAN, serta RAD turunannya, untuk memahami bahwa aman bagi perempuan adalah dari segala bentuk kekerasan baik saat konflik yang tidak otomatis bebas kekerasan saat konflik berakhir.
Relasi gender dan tantangan“politik kehadiran” perempuan:
Politik kehadiran perempuan memiliki makna tidak hanya sekedar kehadiran fisik, namun juga kehadiran yang membawa warna dan makna dengan mempengaruhi keputusan yang lebih adil gender. Pengalaman keterlibatan perempuan telah menunjukkan bukti, kualitas dan responsivitas kebijakan dan keputusan yang diambil dalam kaitannya dengan penanggulangan konflik. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan tentang ketidakadilan gender dalam konteks konflik ini : 1). Upaya penanganan dan pencegahan konflik yang masih bersifat maskulin sehingga kerap mengesampingkan pengalaman dan partisipasi perempuan. Perempuan belum sepenuhnya memiliki posisi tawar yang setara sebagai juru damai walau dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang persuasif dan berkemampuan menjadi juru damai, namun kerap laki-laki yang tampil melanjutkan negosiasi dan penandatanganan kesepakatan damai di ruang formal (seperti yang terjadi di Aceh), 2). Minimnya peningkatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan perempuan, karena program-program yang ada tidak sedikit yang bias gender, padahal tidak sedikit perempuan yang menginginkan kapasitas lebih seperti pengembangan kepemimpinan termasuk menjadi juru damai dan akses untuk mendapatkan sumber kehidupan, 3). Minimnya ruang-ruang strategis, baik ruang aman bagi perempuan korban, ruang perjumpaan untuk berdiskusi, berjejaring, dan berpartisipasi dalam negosiasi damai, 4). Budaya patriarki yang mengakar, sehingga menghambat keterlibatan dan tumbuhnya kepemimpinan perempuan. Bentuknya bisa dilihat dari minimnya pengakuan akan potensi dan bukti kepemimpinan perempuan, hingga tantangan berbasis gender yang menghalangi partisipasi perempuan -seperti pembagian kerja dan ruang berbasis gender dan tersedotnya perempuan dalam kerja domestik yang dianggap tak bernilai (unpaid care works) yang membatasi kehadiran dan pengaruh perempuan dalam pengambilan keputusan
Diskoneksi kebijakan dan pelaksanaan:
1). Sejumlah daerah belum menurunkan Rencana Aksi Nasional kedalam Rencana Aksi Daerah dan merasa perlu mengkaji lebih jauh substansi RAN P3AKS, karena RAN tersebut belum populer di sejumlah wilayah bahkan belum pernah didengar oleh masyarakat. 2). Kompleksitas Koordinasi Pusat dan Daerah. Selama ini tim koordinasi RAN P3AKS di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota masih belum optimal dalam melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN guna menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik. Selain sinergi dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, tata kelola yang transparan dan berintegritas juga dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik, serta dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak. Lemahnya implementasi RAN/RAD juga terlihat dari lemahnya integrasi RAN/ RAD ke dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran baik di pusat maupun di daerah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, mempengaruhi efektivitas agenda perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial. Belum mapannya koordinasi pusat dan daerah ini juga membuat belum adanya pengukuran evaluasi dan monitoring yang dilakukan secara berkala dengan standar yang jelas.
Isu Lokalitas dan dukungan terhadap inisiatif komunitas:
RAN dan RAD diharapkan lebih responsive dengan konteks lokal. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tipologi konflik dan budaya di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu inisiatif-inisiatif dari komunitas khususnya inisiatif perempuan tidak sedikit yang menarik untuk membangun damai dan penting mendapat dukungan, termasuk mekanisme adat maupun inisiatif kultural yang tumbuh di berbagai wilayah. Tidak sedikit pendidikan damai, membangun ruang untuk kohesi sosial, pemulihan korban, dll. Kontribusi dan insiatif damai perempuan menjadi pilar penting ketika masyarakat menghadapi konflik, namun sayangnya, kontribusi ini tidak cukup direkognisi dalam proses formal penanggulangan konflik sosial
Pelibatan berbagai elemen masyarakat yang belum optimal
Dalam diskusi ditemukan permasalahan kurangnya pelibatan masyarakat sipil, padahal keikutsertaan pelbagai lembaga dan organisasi masyarakat sipil, khususnya organisasi perempuan di daerah dalam perumusan RAD menjadi kunci agar mendapatkan legitimasi dan komitmen berbagai pihak, sehingga kebijakan tersebut dapat diterapkan secara optimal. Keikutsertaan seluruh pemangku kepentingan juga perlu dilakukan untuk evaluasi periodik RAN dan RAD.
Minimnya sosialisasi rutin dan internalisasi berbagai pihak
Untuk mengembangkan pemahaman bersama masyarakat dan berbagai lembaga pemerintah atas pilar-pilar P3AKS diperlukan upaya komunikasi rutin. Pemahaman dan internalisasi berbagai pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar terdapat komitmen yang mendukung pelaksanaan dengan misalnya kesediaan untuk mengalokasikan dana dan menjalankan program dalam RAD secara efektif dan sesuai tujuan.
Persoalan komitmen, kesinambungan dan kepemimpinan daerah
RAN telah diadopsi menjadi RAD yang diterima oleh pemerintah daerah di 10 provinsi (per 2019 provinsi yang memiliki RAD adalah Bengkulu, Lampung, Jatim, Kalbar, Maluku, NTB, NTT, Papua, Sulteng dan Sulut). Hal ini menunjukkan terbangunnya komitmen daerah yang melihat urgensi RAD bagi penanganan konflik sosial dengan menggunakan perspektif gender. Harus disadari, bahwa capaian ini belumlah optimal, terutama karena belum semua provinsi dan kabupaten kota di Indonesia memiliki rancangan RAD P3AKS. ementara itu, di daerah yang sudah memiliki rancangan RAD, pengetahuan dan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat masih rendah untuk mendorong hadir dan dilaksanakannya rencana tersebut. Seperti misalnya terdapat kecurigaan bahwa RAD P3AKS mengancam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Perkembangan RAD P3AKS untuk dapat diterima dan memiliki komitmen untuk dilaksanakan dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan daerah. Beberapa daerah yang cukup efektif dan optimal dalam melakukan pembahasan dan pelaksanaan Rencana Aksi adalah Sulawesi Tengah yang memiliki kepemimpinan daerah yang peduli mengenai masalah pemulihan, penanganan dan pencegahan konflik yang berperspektif gender. Namun terdapat daerah lain di mana perkembangannya belum optimal, seperti di Maluku yang sudah memiliki RAD tapi belum proaktif bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil sehingga dampaknya belum menyeluruh. Faktor rotasi pemangku kebijakan yang bertugas menjalankan RAN/RAD di daerah juga berdampak pada efektivitas dan optimalisasi implementasi. Ditemukan bahwa seringkali tidak ada kontinuitas diskusi dan pemahaman substansi RAN, sehingga sering kali tidak ada kesinambungan kebijakan antara satu periode pemangku kepentingan dengan yang sebelum dan selanjutnya.
Dampak konflik yang beragam dan spesifik
Selain kajian spesifik wilayah, perlu juga melihat kekhasan dampak konflik bagi kelompok, komunitas hingga individu yang memiliki perbedaan kebutuhan dan kondisi. Dampak konflik terhadap perempuan dan anak berbeda-beda. Selama ini program penanganan konflik menganggap kebutuhan setiap individu/kelompok di setiap daerah adalah sama dan belum mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kebutuhan spesifik setiap individu/kelompok. Sehingga diharapkan program penanganan konflik dirumuskan berdasarkan pada pendataan dan pemetaan tingkat kerentanan dan kebutuhan individu/kelompok. Salah satu kegagalan dalam menyusun strategi pencegahan konflik antara lain karena pemerintah daerah belum dapat mengidentifikasi tipologi konflik yang berpotensi muncul di wilayahnya.
3.2. Poin-Poin Kesimpulan Berdasarkan Pilar
3.2.1. Pilar Pencegahan
Di bawah pilar pencegahan, terdapat pembahasan mengenai kurang optimalnya upaya peringatan dini (early warning system) yang diimplementasikan sejauh ini, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebelum konflik ter-eskalasi. Untuk membuat sistem peringatan dini yang efektif, perlu untuk memperhatikan kearifan lokal untuk merumuskan pencegahan konflik yang lebih persuasif, serta melibatkan potensi perempuan dan anak yang ada di daerah. Sayangnya, belum semua daerah memiliki data mengenai kondisi dan potensi perempuan dan anak yang diperbaharui secara berkala.
3.2.2. Pilar Penanganan dan Pemulihan
Perlindungan fisik harus diperhatikan untuk menghentikan korban jiwa lebih banyak lagi dalam konflik sosial. Salah satu cara adalah dengan adanya rumah aman dengan fasilitas kesehatan mendukung yang lokasinya terjangkau bagi korban perempuan dan anak, serta adanya bantuan bagi korban untuk menjangkau rumah aman jika diperlukan. Dalam diskusi ditemukan bahwa belum tersedianya rumah aman, khususnya di tingkat desa, sebagai salah satu kendala dalam penanganan korban konflik sosial. Perlu juga perlindungan hukum bagi pendamping korban dan perempuan pembela HAM untuk memastikan bahwa mereka tidak dikriminalisasi dalam melakukan pekerjaan mereka.
Selain konflik berdampak pada kondisi fisik dan ekonomi, terdapat juga dampak psikologis dari konflik. Perempuan dan anak secara khusus terdampak dari konflik karena posisi dan peran mereka di masyarakat. Beban domestik dan fungsi sosial yang diberikan kepada perempuan menjadi bertambah dengan hilangnya anggota keluarga karena konflik. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk menikmati masa tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan. Selain itu juga terdapat perasaan ketakutan atas kekerasan yang dapat terulang, kecemasan atas ketidakjelasan masa depan dan trauma yang membatasi aktivitas. Saat terjadi konflik sosial, perempuan dan anak mengalami tekanan psikis, ancaman dan intimidasi sehingga mereka mengalami trauma. Oleh sebab itu, ke depannya RAN P3AKS diharapkan mampu untuk mengikutsertakan program untuk mengatasi dampak psikologis dari konflik.
3.2.3. Pilar Pemberdayaan dan Partisipasi
Meski sering sekali dipandang sebagai korban, perempuan dan anak perlu dipandang sebagai aktor yang dapat berperan dalam membangun damai dan pemulihan paska konflik. Kontribusi dan pengaruh perempuan dalam inisiatif damai ditunjukkan dari bukti-bukti di berbagai konteks konflik di Indonesia, seperti di Aceh dan Ambon. Sayangnya, kontribusi ini sering tersembunyi dan tidak cukup mendapatkan rekognisi dalam proses formal penanggulangan konflik. Pengakuan ini merupakan dasar bagi pemberdayaan dan pemberian ruang partisipasi bagi perempuan dan anak dalam pengambilan keputusan yang berdampak bagi wilayah konflik dan paska konflik. Satu hal baru yang bisa diikutsertakan dalam RAN selanjutnya adalah perspektif hak anak, baik sebagai korban dalam konflik sosial yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan serta hak untuk berpartisipasi secara substantif dalam proses perumusan kebijakan yang membuatnya lebih inklusif dan berjangka panjang.
Upaya pemberdayaan dan partisipasi perempuan untuk penciptaan perdamaian perlu mempertimbangkan pendekatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi memiliki peluang untuk tak hanya meningkatkan kesejahteraan, namun juga bisa menjadi ruang perjumpaan, membangun dialog, membuka sekat sosial dan pada gilirannya, berkontribusi dalam meredam konflik dan menciptakan perdamaian. Secara spesifik, pemberdayaan ekonomi perempuan akan mendorong relasi kuasa yang lebih adil di tingkat rumah tangga dan komunitas. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan penghasilan keluarga. Pemberdayaan ekonomi mendorong perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan membangun kohesi sosial dengan menggunakan kerjasama ekonomi sebagai alat komunikasi antar komunitas seperti yang dilakukan di Poso, Ambon. Keterkaitan antara pemberdayaan ekonomi dan partisipasi perempuan dalam penanggulangan konflik, menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat.
3.3. Potensi Konflik Masa Datang
Ekstremisme Kekerasan dan Terorisme
Mengatasi potensi konflik di masa depan, penting untuk mewacanakan metode pencegahan dan penanganan radikalisme yang menjurus pada ekstremisme kekerasan dan terorisme. Ada kecenderungan wilayah konflik dan paska konflik rentan menjadi tempat berkembangnya ideologi radikal dan melahirkan kekerasan baru. Peraturan daerah diskriminatif yang masih ada di beberapa daerah justru dapat digunakan oleh kelompok radikal untuk menghasut kebencian antar kelompok yang dapat menempatkan perempuan dan anak sebagai korban. Implementasi ran P3AKS belum bisa menjadi alat pencegahan untuk kekerasan pada perempuan dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan agama sebagai alat kekuasaan
Isu penting lainnya yang perlu diangkat dalam penanganan ekstremisme kekerasan adalah pendekatan militeristik dalam penanganan terorisme, juga terhadap deportan maupun mantan kombatan yang kembali dari Suriah, selain anak-anak mantan teroris dan mantan narapidana teroris yang tidak terintegrasi dengan baik di masyarakat. Di tambah lagi, pendekatan berbasis gender belum menjadi paradigma dalam kebijakan kontra radikalisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme. Untuk itu, upaya untuk mendorong sensitivitas gender dapat dilakukan dengan memasukan upaya penanganan radikalisme kekerasan ke dalam RAN dan RAD P3AKS ke depannya.
Pandemi Covid-19 dan Bencana
Potensi konflik yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan bencana lainnya yang mampu meningkatkan potensi konflik sosial karena memburuknya perekonomian, ketidaksetaraan di masyarakat dan diskriminasi gender, terlihat dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, beban kerja yang meningkat bagi perempuan dan pembelajaran jarak jauh melalui internet namun aksesnya masih terbatas. Diskusi mengenai pandemi menyoroti belum siapnya RAN P3AKS dalam menangani konflik sosial yang disebabkan oleh bencana dan kondisi darurat. Pandemi Covid-19 diharapkan menjadi kesempatan untuk mengikutsertakan penanganan krisis dalam konflik sosial ke Rencana Aksi di masa datang. Hal ini dapat dilakukan dengan menekankan peran yang dapat dilakukan perempuan selama krisis dan keadaan darurat, pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan, serta mendorong perlindungan hak asasi manusia, hak-hak perempuan dan anak.
Perkembangan Teknologi dan Informasi
Kajian mengenai perkembangan teknologi dan informasi disoroti juga sebagai ruang potensi konflik baru, khususnya mengenai penyebaran informasi tidak benar (hoaks), intoleransi dan radikalisme. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi, menempatkan jurnalisme menjadi sarana penting dalam membangun narasi perdamaian dan kesetaraan gender yang mempengaruhi persepsi masyarakat tentang konflik, peran perempuan, dan kesetaraan. Dalam pembahasan terlihat bahwa perlu diadakan pengarusutamaan gender dan perdamaian yang melibatkan jurnalis agar media punya kapasitas jurnalisme damai dan sensitif terhadap isu gender.
4. Rekomendasi
Bagian rekomendasi ini terbagi menjadi tiga bagian besar, yakni Rekomendasi Umum, Rekomendasi Isu-isu Tematik dan Rekomendasi Berbasis Pilar.
4.1. Rekomendasi Umum
A. Pemetaan yang cermat dan berbasis data
- Memetakan pola konflik dan metamorfosisnya, untuk melihat pola baru, pergeseran yang terjadi dan keterhubungan antar konflik masa lalu dan yang terjadi saat ini.
- Membuat data dan analisa komprehensif tentang isu, akar dan pemicu konflik serta dampaknya terutama terhadap kelompok rentan, utamanya perempuan, termasuk melihat dampaknya di ranah privat
- Membuat indikator wilayah konflik, paska konflik dan wilayah rentan konflik
- Membuat skema pencegahan, perlindungan, pemberdayaan dan pemulihan korban dengan indikator yang berkeadilan gender
- Membuat data kebutuhan korban konflik dengan menimbang interseksi atas kelompok rentan diskriminasi
- Hindari kesalahan diagnosis yang berdampak pada kekeliruan prognosis yang berdampak pada program penanggulangan yang tidak efektif.
B. Membangun arsitektur penanggulangan konflik yang komprehensif dan memperluas makna keamanan
- Mengedepankan prinsip HAM dan keadilan gender khususnya dalam merumuskan substansi kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan konflik
- Meminimalisir keterlibatan militer dan mencegah pendekatan militeristik yang represif dalam penanganan konflik yang cenderung berdampak multi generasi
- Mengedepankan perlindungan atas kehidupan, di atas segalanya, di tengah kebutuhan akan state security
- Perlu pendekatan interdisiplin ilmu dalam menanggulangi konflik, termasuk dalam konteks terorisme. Paradigma keamanan saja tidak cukup, namun harus melihat interseksinya dengan isu-isu lain
- Pendekatan pembangunan yang harus berorientasi untuk meningkatkan resiliensi dan partisipasi
- Memasukkan kurikulum gender dalam pendidikan sektor keamanan termasuk memastikan afirmasi perempuan dapat duduk dalam posisi strategis pada institusi pertahanan dan keamanan
- Menumbuhkan keterlibatan dan kepemimpinan perempuan dalam ruang-ruang strategis dan berbagai pilar pilar dalam RAN P3AKS dan dalam arsitektur penanggulangan konflik
C. Menumbuhkan inisiatif perdamaian berbasis komunitas dengan proses yang mengakar dan inklusif
- Memahami keunikan konteks lokal dan merawat inisiatif-inisiatif maupun tradisi berharga untuk perdamaian yang hidup di masyarakat
- Sosialisasi kebijakan hingga ke tingkat desa, mengingat konflik semakin terbuka di desa, serta memperkuat kemampuan aktor-aktor masyarakat khususnya di desa untuk menjadi agen perdamaian
- Pelibatan elemen masyarakat, utamanya perempuan, anak muda termasuk namun tapi tidak terbatas kelompok-kelompok rentan diskriminasi
- Pengakuan akan kontribusi baik aktor negara maupun non negara dalam upaya-upaya membangun perdamaian
- Mencari solusi damai yang tidak segregatif dengan memisahkan masyarakat yang menghalangi interaksi dan perdamaian yang berkelanjutan
D. Menciptakan penanganan dan birokrasi yang responsif, sinergis dan peka konteks
- Mempertimbangkan konteks daerah yang sangat beragam, sebagai pijakan dalam perumusan RAN ke depan, baik berbagai konteks konflik yang terjadi, isu dan relasi sosial, politik dan budaya, serta melihat implikasinya pada kehidupan perempuan dan anak
- Memastikan interkoneksi antar kebijakan, tidak kontradiktif dan konsisten dari nasional hingga ke daerah tak terkecuali hingga tingkat desa
- Memastikan pelaksanaan RAN dan RAD dilakukan secara komprehensif, sinergis antar kementerian dan seluruh jenjang birokrasi hingga ke desa dengan pelibatan masyarakat sipil dan pihak-pihak strategis lainnya, termasuk perempuan untuk membangun rasa kepemilikan dan komitmen kolektif
- Memastikan peran kepemimpinan daerah berjalan dengan efektif, termasuk memastikan keberlanjutan pengetahuan dan kebijakan akibat sistem rotasi pemangku tanggung jawab dalam birokrasi
- Memastikan RAD yang responsif dan antisipatif pada konflik, yang berlapis dengan isu terorisme, bencana hingga situasi pandemik
E. Menumbuhkan kepemimpinan perempuan dan keterlibatan yang strategis
- Mengoptimalkan peran-peran kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dengan “politic of presence” sebagai aktor perdamaian dengan peran yang tidak meresikokan keamanan, integritas hingga beban berlipat karena peran gendernya.
- Memperluas ruang pengakuan atas peran dan kepemimpinan perempuan yang tidak terbatas di ruang formal, tetapi juga pengakuan di ruang informal, kultural, bahkan peran perempuan di ruang domestik untuk melindungi kehidupan, bertahan dalam krisis akibat konflik dan mentransmisikan perdamaian pada keluarganya
- Melibatkan perempuan khususnya perempuan korban dengan memastikan keterjangkauan mereka atas jarak, akses informasi teknologi, bahasa, disabilitas, juga sensitif pada isu relasi kuasa karena gender maupun kelas dalam masing-masing komunitas, juga kerentanan karena identitas lainnya.
- Pengakuan terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM serta perlindungan dari kriminalisasi dan kerentanan lainnya.
F. Perlindungan pada kelompok rentan diskriminasi dan korban kekerasan
- Perempuan pembela HAM dari kriminalisasi, stigmatisasi hingga resiko keamanan nyawa
- Perempuan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual akibat konflik termasuk kekerasan di ranah komunitas maupun ranah domestik yang cenderung berpindah lokus dan meningkat paska konflik
- Kelompok disabilitas yang kerap tidak dijadikan prioritas saat evakuasi baik saat konflik maupun bencana
- Kelompok “minoritas” agama/kepercayaan, termasuk yang menjadi korban penyesatan agama, yang kehilangan hak dasar hingga menjadi pengungsi
- Kelompok dengan orientasi seksual non-hetero, yang menjadi sasaran politisasi dan persekusi
G. Membangun kesadaran kritis di semua ranah
- Pendidikan multi jenjang sejak dari PAUD hingga perguruan tinggi tentang pluralisme, toleransi dan perdamaian termasuk konstruksi berkeadilan gender untuk mengikis maskulinitas yang tidak sehat (toxic masculinity) yang berkontribusi memicu konflik dan kekerasan
- Memperkuat daya tahan keluarga dari pengaruh konservatisme hingga terorisme
- Memperluas jurnalisme warga (citizen journalism) dan jurnalisme damai (peace jurnalisme) untuk mencegah ujaran kebencian yang memicu maupun mempertahankan konflik destruktif
- Penyadaran literasi digital, termasuk pada perempuan, agar kritis untuk memastikan kebenaran informasi (bukan hoaks), terhindar dari kekerasan berbasis siber, dan dapat menggunakan dunia siber untuk membangun perdamaian dan peradaban baru yang keadilan gender
4.2 Rekomendasi Isu-isu Tematik
A. Penanggulangan ekstremisme berkekerasan/terorisme dengan menggunakan perspektif HAM-perempuan
- Menelusuri akar persoalan baik politik, sosial, ekonomi, teologis hingga persoalan psikologis, di balik mereka yang terlibat dalam gerakan ekstrimisme khususnya di balik para pelaku terorisme, tak terkecuali dimensi dan konstruksi maskulinitasnya
- Analisis baru tentang interseksi ekstrimisme dan konflik sangat bermanfaat untuk membaca akar-akar baru konflik, kedukaan (grievances) yang perlu direspon sebelum berubah jadi konflik atau ekstremisme
- Memetakan secara tepat persepsi kelompok-kelompok radikal terhadap posisi negara dan melihat kelompok yang masih dipercaya khususnya elemen non-pemerintah dengan penekanan pada penciptaan ruang-ruang dialog bersama antar warga.
- Memastikan penanggulangan yang dilakukan mengedepankan perlindungan atas kehidupan, mengedepankan kemanusiaan dan efek jangka panjang
- Pendekatan keamanan insani dalam semua lapis penanggulangan terorisme tanpa mengesampingkan penindakan hukum bagi pelaku kekerasan
- Pelaku maupun korban harus diperlakukan sebagai warga negara yang tidak bisa dihilangkan hak dasarnya, atas perlakuan yang bermartabat baik di hadapan negara/hukum maupun di masyarakat
- Perlu ada koordinasi antar kelembagaan dalam penanganan terorisme, termasuk bersinergi dengan organisasi masyarakat sipil. Namun forum-forum masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah perlu diperjelas tugas dan fungsinya agar tidak tumpang tindih, karenanya penting memetakan kapasitas masyarakat sipil agar ada sinergi yang optimal
- Memastikan ada pemulihan komunal selain pemulihan individual, menghilangkan stigmatisasi dengan penerimaan, termasuk dukungan komunal atas pengasuhan alternatif pada anak-anak, juga dukungan dari keluarga (family support system)
- Memastikan ada rehabilitasi dan integrasi bahkan langkah ke depan (paska tindakan terhadap terorisme), karena adanya “dosa kolektif” yang harus ditanggung berbagai pihak bila masalah terorisme tidak ditangani melalui penghargaan hak asasi
- Memperkenalkan rujukan keagamaan yang moderat dan adil gender
- Memastikan lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang memuat nilai perdamaian, termasuk dalam pendidikan keluarga
- Memastikan adanya keterkaitan antara kebijakan pencegahan ekstremisme kekerasan (preventing violent extremism – PVE) dengan RAN P3AKS agar upaya mendorong pengarusutamaan gender dalam PVE bisa dilakukan dengan maksimal, ini karena RAN P3AKS telah memiliki infrastruktur di tingkat provinsi
- Kebijakan terhadap tindak pidana terorisme pada UU No. 5 tahun 2018 dan turunannya harus mengintegrasikan perspektif gender dengan kuat
- Pemerintah perlu memastikan korban konflik, utamanya perempuan, bisa mendapatkan pemulihan komprehensif dan berjangka panjang, baik pemulihan sosial, ekonomi, maupun psikis yang bersifat individual maupun pemulihan kolektif bersama komunitasnya
- Penguatan keamanan siber pada aktor-aktor yang bekerja di isu PVE sangat penting karena aktivitas radikalisasi di dunia maya meningkat pesat di masa pandemi, serta kemungkinan salah satu strategi untuk melumpuhkan situs-situs yang kontra pada gerakan ekstrimis sedang dilancarkan
- Memantau deportan dan returni untuk cegah aksi-aksi teror kembali, maka mewaspadai daerah yang pernah mengalami konflik terbuka atau daerah rawan konflik
- Memastikan inklusi pada pemimpin perempuan dan organisasi perempuan akan berpotensi untuk menciptakan perdamaian jangka panjang, baik di ranah publik maupun domestik, antara lain meningkatkan peran keluarga untuk mencegah radikalisme, termasuk pelibatan istri dan keluarga dalam mendukung keterlepasan dari kelompok radikal (disengagement)
- Review sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dan anak dalam konflik sosial — antara lain kebijakan UU no 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Perpres no 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, serta Permenko Kesra no 8 tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial — tidak mengatur secara spesifik isu terorisme. Selain itu UU no 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme yang tidak mencantumkan kata perempuan, gender, kecuali dalam pencegahan
B. Konflik Sumber Daya Alam (SDA)
- Memasukkan konflik SDA kedalam RAN P3AKS tahap selanjutnya, karena konflik SDA sulit dijangkau dengan RAN P3AKS
- Mencari solusi atas konflik SDA yang cenderung deadlock penyelesaiannya
- Audit perusahaan dan penegakan hukum
- Memastikan prinsip penjuru (guiding principle) dalam kaitan berjalannya bisnis yang menghargai HAM dapat dijalankan melalui pelaksanaan RAN tentang bisnis dan HAM
C. Konteks Pandemi dan Bencana
- Menutup peluang bagi tumbuhnya konflik sosial dan radikalisme yang memanfaatkan situasi pandemi dan bencana
- Memastikan bantuan dalam penanganan pandemi dan bencana terdistribusi dengan adil untuk mencegah munculnya konflik
- Memastikan pembagian bantuan penanganan pandemi dan bencana yang adil gender, tidak hanya untuk laki-laki yang diposisikan sebagai kepala keluarga
- Hentikan kekerasan berbasis gender serta meningkatnya kerentanan perempuan karena beban perempuan bertambah
- Prioritaskan penanganan korban konflik yang juga terkena dampak pandemi karena mereka belum tertangani sebagai korban konflik namun sudah menjadi korban lanjutan pandemi
4.2. Rekomendasi Berbasis Pilar
A. Rekomendasi untuk Program Pencegahan
- Kajian tipologi konflik sebagai pijakan untuk mendesain pencegahan yang efektif dengan melihat kerentanan, kebutuhan dan kekhususan yang berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain
- Pemberdayaan bagi perempuan dan anak agar dapat berperan aktif dalam membangun kerukunan dan toleransi, antara lain dengan pendidikan yang menghargai perbedaan baik dalam pendidikan formal maupun informal, termasuk pendidikan tentang adil gender dengan menyoal maskulinitas yang memicu kekerasan
- Membuat pendidikan bagi media untuk membuat pemberitaan yang merawat perdamaian dan berperspektif gender
- Peningkatan daya tawar perempuan salah satunya kemampuan ekonomi bagi perempuan untuk membangun kohesi sosial
- Dukungan pemulihan psikis untuk mencegah korban tidak menjadi pelaku dan memicu keberulangan konflik
- Membuat mekanisme partisipatoris yang menjamin keikutsertaan perempuan dan anak dalam pengambilan kebijakan, termasuk kelompok muda, disabilitas, juga anak-anak, dalam pencegahan konflik termasuk radikalisme dengan kekerasan
- Memastikan ada memorialisasi di wilayah-wilayah rentan konflik, khususnya paska-konflik sebagai simbol pemulihan korban, hak kebenaran dan mencegah keberulangan
- Mendorong parlemen untuk membuat kajian atas UU P3AKS dan RAN terkait, serta dukungan untuk peningkatan anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan praktis dan strategis terkait P3AKS
B. Rekomendasi untuk Program Penanganan
- Memastikan Tim Terpadu Kemendagri melakukan sosialisasi dan internalisasi tentang RAN-P2AKS, punya kemampuan mediasi dan punya keberpihakan terhadap perempuan pembela HAM
- Memberi perlindungan hukum bagi pendamping korban dan perempuan pembela HAM untuk memastikan bahwa mereka tidak terkriminalisasi dalam melakukan pekerjaan mereka.
- Menjamin perempuan dapat mengakses dukungan penanganan tanpa terhalang oleh persyaratan karena jenis pekerjaan yang dimiliki
- Memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan dasar seperti kesehatan, lapangan kerja yang tepat, serta peningkatan kemampuan untuk berorganisasi dan menjadi juru damai
- Penguatan kelembagaan termasuk lembaga sipil dan organisasi masyarakat, organisasi keagamaan dengan memastikan prinsip imparsialitas, mediasi, kemampuan pembangunan perdamaian, dan utamanya paham substansi RAN P3AKS
- Perlu adanya rumah aman di setiap desa atau setidaknya bantuan transportasi yang mampu membawa korban konflik, khususnya perempuan dan anak, ke rumah aman terdekat
- Penanganan untuk korban konflik dan paska konflik, khususnya perempuan dan anak, tidak hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, namun juga psikis. Termasuk memastikan data korban, data disabilitas, kelompok minoritas dan kelompok rentan diskriminasi lainnya
- Memberi pemahaman sensitif gender dalam penanganan konflik bagi aktor keamanan, serta pengetahuan atas UU P3AKS dan RAN, serta RAD turunannya agar dapat bekerja secara sinergis dalam membangun perdamaian
C. Rekomendasi untuk Program Pemberdayaan dan Partisipasi
- Mengadopsi RAN menjadi RAD yang dilembagakan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikawal melalui proses afirmasi perempuan dalam musrenbang , penguatan kapasitas bagi perempuan dan anak, sebagai strategi untuk memastikan partisipasi yang bermakna di semua tingkatan.
- Mendorong adanya panutan (role model) dan agensi perempuan dalam pemberdayaan, partisipasi dan membangun kerekatan untuk perdamaian melalui kanal-kanal yang mengakar di komunitas baik melalui keberdayaan ekonomi sebagai kekuatan negosiasi maupun ruang budaya yang mudah dijangkau perempuan akar rumput
- Mendorong keterlibatan laki-laki dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender, karena mensyaratkan proses dialog untuk menata ulang relasi yang selama ini tidak adil. Sebab, penyadaran kritis tentang adil gender adalah urusan bersama
- Peningkatan kapasitas mediasi konflik dan pembangunan perdamaian yang sensitif gender yang tertulis di dalam kebijakan (mulai dari Perpres, Pergub, Perbup dan seterusnya) sehingga memiliki kekuatan hukum, kemampuan implementasi dan komitmen pendanaan
- Pentingnya memasukkan perspektif hak anak, baik pemenuhan hak sebagai korban, perlindungan hingga pengasuhan termasuk keterlibatan substantif sesuai dengan tumbuh kembang anak
- Perlu adanya kriteria/indikator keterlibatan perempuan dan anak dalam upaya-upaya perdamaian, resolusi konflik dan mekanisme perjanjian perdamaian, serta ketersediaan informasi secara berkala mengenai potensi perempuan dan anak di berbagai tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten kota, kecamatan desa) dan memastikan peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan di setiap level pengambilan keputusan terkait konflik, termasuk pelibatan anak pada ruang-ruang yang tepat.
- Meningkatkan kapasitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk menangani perempuan dan anak yang menjadi korban konflik

RINGKASAN DISKUSI MINGGU PERTAMA (20-26 Juli 2020) – Perlunya mengkontekstualisasi RAN P3AKS ke depan dengan mengikutsertakan perkembangan di tingkat global yang berdampak pada kerentanan nasional dan daerah yang dapat memicu konflik sosial. – Perlunya kontekstualisasi RAN di tingkat daerah yang didukung dengan adanya (1) sosialisasi kerangka dan pedoman kerja RAN ke tingkat lokal dengan penyesuaian kondisi wilayah dengan pencapaian yang terukur, (2) berjalannya koordinasi antar kementerian/lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, (3) penyesuaian program aksi daerah dengan kebutuhan berdasarkan situasi konflik yang ada di… Read more
RINGKASAN DISKUSI MINGGU KEDUA (27 JULI-2 AGS 2020) Poin-poin persoalan ; – Hasil simpulan dari pengalaman pendampingan komunitas untuk konteks konflik sosial di Aceh, Deli Serdang dan Karo. – Konflik komunal saat ini semakin banyak terjadi di desa, namun kapasitas penyelesaian sangat senjang, karena pembangunan cenderung berorientasi fisik dibanding membangun kapasitas termasuk merespon konflik. – Minim sosialisasi kebijakan hingga tingkat desa, termasuk RAN P3AKS di wilayah diatas. Termasuk tidak diturunkan dalam RAD . Hal ini adalah bentuk diskoneksi kebijakan nasional dan daerah, padahal RAD sebagai penjembatan implementasi. – Isu HAM dan gender tidak diinternalisasi dalam proses membuat dan menjalankan kebijakan, sehingga berdampak pada… Read more
RINGKASAN DISKUSI MINGGU KETIGA (3-9 Agustus 2020): Poin persoalan: Dalam menghadapi wilayah konflik, pendekatan militerisme kurang tepat karena menyebabkan meningkatnya konflik sosial dengan menimbulkan masalah baru khususnya di daerah Nduga, Paniai, Jayapura, Wamena, Timika, Manokwari, Sorong, dan Fak-Fak Terdapat permasalahan mengenai isu rasisme dan pendekatan tuntutan hukum terhadap individu dan kelompok yang menyuarakan pendapatnya, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat Adanya dampak teknologi terhadap konflik sosial melalui penyebaran informasi yang salah/kurang tepat, dampak khusus dialami oleh perempuan melalui pemberitaan yang kurang sensitif gender Adanya perbedaan akses teknologi dan informasi (digital divide) yang semakin diperburuk oleh pandemi Pandemi Covid-19… Read more
RANGKUMAN MINGGU KE-4 ; Isu yang berkembang pada minggu ke 4 sejak 20 Agustus 2020 adalah; – Analisa atas relasi kuasa yang timpang, sedapat mungkin memasukkan tipe-tipe konflik seperti konflik ideologi dan konflik masyarakat sipil dengan aktor pemerintah (misalnya polisi, militer) – Isu ekonomi sebagai dampak konflik khususnya pandemi, termasuk perhatian khusus terhadap ketimpangan ekonomi dalam konflik yang menyempitkan distribusi kesejahteraan – Agensi perempuan ; suara perempuan yang tidak didengar, perempuan diposiskan sebagai korban padahal tidak jarang sebagai aktor yang konteibutif – Minimnya data di wilayah konflik ; termasuk data korban, data disabilitas baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta – Isu tehnologi ;… Read more
Selamat datang di konsultasi digital nasional Review RAN P3AKS. Perkenalkan, nama saya Fitriani dan bersama mbak Yunianti Chuzaifah kami adalah moderator Ruang Diskusi 5 mengenai Rekomendasi Publik. Ruang diskusi ini bertujuan untuk bersama-sama mengumpulkan masukan untuk merumuskan kelanjutan dari Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) tahun 2014-2019. Karena keberlanjutan dari RAN P3AKS ini sangatlah penting bagi perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang berada dalam konflik sosial di Indonesia, kami mengharapkan partisipasi aktif rekan-rekan dalam konsultasi digital nasional ini. Untuk memudahkan diskusi, rekan-rekan dapat menjawab pertanyaan panduan di atas, baik seluruhnya, atau memilih… Read more
Selamat datang kawan- kawan semua, kita masuk ke dunia experimental, melakukan review dengan cara virtual, tetapi sistematis dan mengacu seperti yang dilakukan PBB. Selamat berdiskusi dengan aktif, berdata, dan menggulirkan rekomendasi- rekomendasi penting, untuk jadi pilar-pilar penting Kelanjutan RAN P3AKS kedepan.
Saya kira adaptasi 1325 di dalam RAN dan diperluas dengan isu konflik sosial merupakan sebuah adaptasi isu nasional dan global. berkaitan dengan hal tersebut perkembangan teknologi tidak dapat dihindarkan. Perempuan mendapatkan keuntungan sekaligus juga berada pada posisi rentan. Perempuan sebagai pengguna gadget dibanjiri oleh informasi, namun bagaimana reaksinya, kajian tentang penggunaan WA menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi konsumer, dia membaca dan memforward isinya. Tidak jarang isinya adalah merentankan perempuan lainnya misalnya body shaming, mengudarakan bentuk tubuh yang dianggap aneh atau tidak biasa. Adakah ini juga kemungkinan dibahas di dalam RAN?
Selamat datang di ruang diskusi 5, selain melalui ketikan di hp/komputer, teman-teman dapat memberi masukan melalu tulisan tangan di kertas lalu difoto atau rekaman suara yang kemudian dimasukkan/diupload ke ruang diskusi ini. Kami sangat menghargai pendapat ibu bapak sekalian, bagaimana pun bentuknya. Salam hangat, Fitri
Seperti yang sudah saya share dalam roo 2, bahwa kerja-kerja awal RAD-P3AKS, di Papua sekitar oktober 2015 dan setelah di tahun 2016 sekitar bulan November, di fasilitasi oleh mba Adriana Venny Aryani – Komnas Perempuan dengan mitra di Jayapura (Dinas P3A Papua, Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan LSM yang focus pada isu perempuan dan anak), saya mau memberikan saran yang akan diolah sebagai rekomendasi nasional, sbb: 1. Sosialisasi, pada tataran ini pihak yang berkewajiban mengelaborasi program harus dilibatkan penuh dan harus ada semacam kerangka kerja yang ditetapkan secara nasional. Kerangka kerja nasional kemudian harus disesuaikan dengan kondisi local wilayah, sehingga di daerah harus ada pedoman kerjanya dalam penanganan P3AKS… Read more
Salam kenal dari Surabaya.
Selamat malam, saya ingin berpendapat mengenai bagaimana sebaiknya P3AKS dilakukan. Pandemi Covid 19 ini sebetulnya merupakan momentum yang diatur oleh Yang Maha Mengatur Hidup Manusia juga Alam Semesta. Ternyata segala hal yang baik berada dan berasal dari rumah. Kita dirumahkan paksa karena situasi. Dipaksa juga untuk memperbaiki situasi rumah dan mengatur keluarga untuk memulai mencintai rumah dengan segala isinya yaitu keluarga. Bukan hal yang baru karena sekian tahun yang lalu program2 pemerintah menetapkan rumah atau keluarga sebagai dasar pelaksanaan program. Itu berarti Ketahanan Sebuah Keluarga lebih penting dari organisasi apapun dan sehebat apapun. Ada banyak program yang dibuat dengan dasar… Read more
Selamat malam kawan-kawan yang sudah seminggu ini menyampaikan pikiran-pikiran untuk meresPon pertanyaan kunci sebagai bahan berharga untuk merumuskan rekomendasi. Seminggu kemarin, mbak Fitri ynag menemani proses diskusi. Minggu ini saya yang gantian jaga ronda. Perkenankan, saya perkenalkan diri lagi, saya yuniyanti chuzaifah, mantan komisioner Komnas Peremouan dan juga jadi board Aman. Mari kawan-kawan yang sudah berkomentar, ditunggu tiap hari ya untuk buka platform digital ini, melengkapi beberapa pertanyaan yg belum direspon, maupun mempertajam, juga menanggapi komentar-komentar lain. Go go go.
Selamat malam Ibu-ibu semua, Salam dari kami lembaga CSO yang bergerak dalam permberdayaan perempuan dan anak, YAPIDI di Sumatera Utara. Maaf baru bisa nimbrung tanggapan di Ruang 5, saya peserta Ruang 3. Ada beberapa hal yang menjadi masukan saya terkait perempuan dan anak dalam konflik sosial sesuai apa yang kami alami dalam pendampingan perempuan dan anak selama ini di Aceh, Kab.Deli Serdang dan Kab.Karo. 1.Sosialisasi terhadap RAN P3AKS di Sumut masih sangat minim serta RAD untuk Sumut dan Kabupaten dibawahnya belum ada sejauh yang kami tahu setelah kami pernah ikuti kegiatan RAN P3AKS di Jakarta setahun silam. 2.Rekomendasi yang menurut… Read more
Perlu adanya pemberdayaan perempuan khususnya bid ekonomi dimana masa pandemi covid 19 ini bnyk perempuan terdampak, khususnya perempuan.jadi perlu bgmn meningkatkan produktifitas yg dilakukan oleh perempuan pelaku usaha industri rumahan, baik perempuan sbg perempuan kepala keluarga maupun perempuan yg membantu suami bekerja unt memenuhi kehidupan keluarga
Terima kasih akan partisipasi teman-teman yang baru bergabung dari ruang diskusi lain. Perkenalkan nama saya Fitriani dan bersama ibu @100 kami memoderatori ruang 5 yang berusaha menggali rekomendasi publik untuk kemajuan RAN P3AKS agar penerapannya bisa menjadi lebih baik, inklusif, relevan dan memiliki kemampuan mitigasi untuk menghadapi berkembangnya situasi yang kita hadapi. Kita berada di minggu ketiga diskusi online dan teman-teman yang baru bergabung dapat penjawab pertanyaan pemantik di atas atau menanggapi diskusi yang sedang berjalan. Teman-teman dapat memberikan masukan untuk tingkat nasional maupun daerah, pengalaman yang dihadapi dari implementasi RAN sejauh ini maupun saran untuk mengikutsertakan hal-hal baru yang… Read more
Status Papua saat ini tidak jelas apa? dalam arti Papua ini DOM kah? Waktu lalu negara sudah menyatakan bahwa Papua bukan lain DOM namun sampai saat ini pendekatan yang di pakai itu militerisme hal ini menjadi penyebab konflik sosial tinggi. konflik tidak pernah selesai dan masalah baru muncul terus misalnya, Nguda, Paniai, Rasisme (Jayapura, Wamena, Timika, Manokwari, Sorong, dan Fak-fak), tambrauw, dan Aifat dan Pasal Makar tumbuh subur di Papua dan Papua Barat.
Rekomendari : Stop Pendekatan Militerisme di Tanah Papua (Papua & Papua Barat)
Informasi tentang RANP3KS bisa terpublis di media pemerintah pusat dan daerah agar masyarakat mengetahui informasi dan perkembangannya
Kelompok muda mohon agar selalu di libtakan dalam isu ini diman anak muda memilki pandangan tentang isu ini

Kelompok rentang dan inkiusi bisa ada data base dan mendaptkan bantuan yang menyeluruh dari masyrakt sipil swasta dan pemerintah
Pemerintah memfasilitasi program program ekonomi buat anak muda dan perempuan yang rentan dan ikusi agar bisa tetap mendaptkan penghasilan di saat covid 19 ini
Perkembangan IT di banyak sisi menghadirkan kemudahan bagi perempuan itu sendiri, memperbanyak cara untuk lebih terampil dalam banyak hal. Namun keberadaan Media sosial sebagai bentuk kemajuan IT tersebut nyatanya juga turut menyumbangkan pergeseran dan perubahan cara penadang terhadap banyak hal, tidak hanya pada persepsi body shaping, namun pada orientasi politik dan pemahaman radikal yang tanpa mereka sadari sepenuhnya. banyak perempuan yang mengonsumsi informasi apapun dari media sosial, copas dan share conten agama dan politik yang cenderung radikal “tanpa berpikir kritis” terlebih dahulu mempengaruhi pandangan perempuan itu sendiri lalu keluarga mereka. seperti yang banyak terjadi pada peempuan yang terjebak dalam kelompok… Read more
Sejak awal masa pandemi perempuanlan yang bergerak lebih dulu dan paling cepat dalam merespon berbagai dampak pandemi, pembagian masker, pembagian bahan makanan, pembelajaran anak di rumah, tanggap lingkungan das sebagainya. RUN P3KS selayaknya tidak hanya memposisikan perempuan sebagai obyek “rentan” namun juga sebaga subyek”penggerak” dalam berbagai persoalan perempuan, anak dan masyarakat itu sendiri.
Satu lagi yang mungkin perlu diperhatikan dalam RAN P3AKS adalah perempuan dan anak berkebutuhan khusus. Saat kami menangani penyintas erupsi Gunungapi Sinabung, dalam aturan yg dibuat dikatakan mereka diprioritaskan. Tapi faktanya tidak. Saya tidak begitu menguasai terkait disabilitas atau berkebutuhan khusus. Mungkin ada CSO atau person yang bisa menambah masukan ini. Terima kasih.
1. Apakah ada isu-isu penting yang harus ada dimasukkan dalam RAN P3AKS yang kedua? Ketidak adilan ekonomi; ketidak adilan gender a. Apakah ada praktek-praktek terbaik yang ditemukan dalam implementasi RAN P3AKS (2014-2019) yang penting untuk dilanjutkan? Konsultasi online dengan durasi waktu yang panjang dan fleksibel dengan support system yang bagus (salut kepada Aman yang sudah melakukannya). b. Apakah ada target RAN P3AKS (2014-2019) yang belum terlaksana atau belum berjalan dengan baik dan perlu untuk dilanjutkan? – c. Apakah ada kelompok perempuan dan anak yang keikutsertaannya dalam RAN P3AKS kedua perlu ditekankan? Korban di wilayah konflik, apakah mereka yang kurang bisa mengakses teknologi online bisa… Read more
Penting kedepan agar ada working grup kerja isu anak dan perempuan yang melibatkan pelbagai lembaga dan juga kelompok anak muda agar ikut menyuarakan isu ini dimana kelompok muda penting untuk di ajak berpatner dalam isu ini
1. Apakah ada isu-isu penting yang harus ada dimasukkan dalam RAN P3AKS yang kedua? Ada, Berbagai isu penting itu adalah: a. Perlu merumuskan ulang tentang definisi konflik, karena konflik dibagi menjadi konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat dalam relasi kuasa yang sama atau serupa, sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara warga masyarakat dengan Pemerintah, militer, kepolisian, dan perusahaan trans/multi nasional yang keduanya memiliki relasi kuasa yang timpang. b. Konflik ideologi, Konflik ideologi ini akan berdampak pada konsep berpikir dan bertindak. Jika relasi kuasa antar kelompok tidak seimbang, maka biasanya pemilik relasi kuasa terbesar yang akan menang. Akibatnya,… Read more
Tanggapan saya atas pertanyaan no. 4. :
Saya mengusulkan perlu
Tanggapan saya atas pertanyaan no.4 Reformasi pendidikan formal Pendidikan kita membutuhkan humanisasi dalam atmofer sekolah/lembaga pendidikan lain. Perlu ada perbaikan dalam pola relasi antara pendidik dan peserta didik, pendidik dengan dinas pendidikan atau pendidik dengan pihak yayasan (untuk sekolah swasta) agar menghilangkan pola relasi kuasa. Perlu mengaktifkan kerjasama lembaga pendidikan, keluarga-keluarga dan masyatakat, dalam penyelenggaraan pendisikan sehingga belajar memliki makna lebih luas, lebih menyentuh pada persoalan hidup konkret dan menumbuhkan partisipasi semua pihak bagi tumbuhkembang generasi muda yang berilmu, berkarakter dan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi. Kurikulum pendidikan harus sungguh-sungguh menghirmati keragaman jenis kecerdasan siswa, mengindari penyeragaman dalam melihat… Read more
Salam kenal, saya Maryanti mahasiswi Damai dan Resolusi Konflik Unhan. Mohon ijin baru bergabung, saya senang sekali bisa belajar banyak dari para senior dan mentor yang telah lebih dulu terlibat dalam perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Sama seperti yang saya sebutkan dalam Ruang Diskusi 4 sebelumnya, saya masih belum banyak pengalaman di lapangan dan lebih kepada hasil belajar. Oleh karena itu, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan sesuai dengan kapasitas dan sifatnya menambahkan karena penjelasan dari Bapak/Ibu/senior semua sudah sangat komprehensif ? 1. Apakah ada isu-isu penting yang harus ada dimasukkan dalam RAN P3AKS yang… Read more
Mohon maaf baru bisa memberikan masukan. Dalam setiap kebijakan untuk ke daerah bisa disisipkan atau menggunakan pendekatan per daerah masing-masing. Sifat di daerah tentu saja berbeda dengan pusat, pun juga berbeda tiap-tiap daerah. Terkadang kebijakan dari pusat dengan kacamata pusat jika diterapkan di daerah kurang bisa optimal. Supaya keberlanjutan kegiatan bisa berjalan dengan baik, jadi tanpa adanya ini sudah otomatis berjalan sendiri. Memang menjadi PR bersama bagaimana membuat kegiatan bisa berkelanjutan, mengingat situasi dan kondisi manusia dan alamnya yang mengalami perubahan. Seperti pandemi covid-19 yang tidak diduga ini yang membuat anak dan perempuan semakin rentan.
Mohon maaf telat ikutan bersuara, setelah saya membaca semuanya akhirnya saya melihat ada yang mengusulkan melibatkan kaum muda dalam pencegahan radikalisme. menurut hemat saya, yang dimaksud anak muda harus spesifik disini adalah anak sesuai UU No. 35 tahun 2014 (UUPA), karena anak sebagai bagian dari kelompok rentan mereka juga bagian yang memiliki hak untuk berpendapat dan juga memiliki kewajiban untuk berbakti dalam pembangunan negara (sesuai dan usia dan kepatutannya). Adanya Forum Anak yang sudah terbentuk dan terstruktur dari pusat hingga daerah dan bahkan dibeberapa tempat hingga tinggkat kelurahan dan RW, adalah bentuk dari pelibatan mereka dalam pembangunan sehingga sepatutnya dalam… Read more
Salam sehat semuanya….saya melihat bahan dan masukannya sangat berarti. Mungkin ini bagian kecil saja, apakah tidak bisa memasukkan elemen bahwa pegiat membutuhkan fasilitasi juga. Mereka yang terjun di isu ini, juga membawa beban pada diri mereka, sehingga mereka juga butuh healing. Saya tidak tahu bagaimana memasukkannya ke dalam usulan atau bisa menjadi agenda diskusi mendatang.